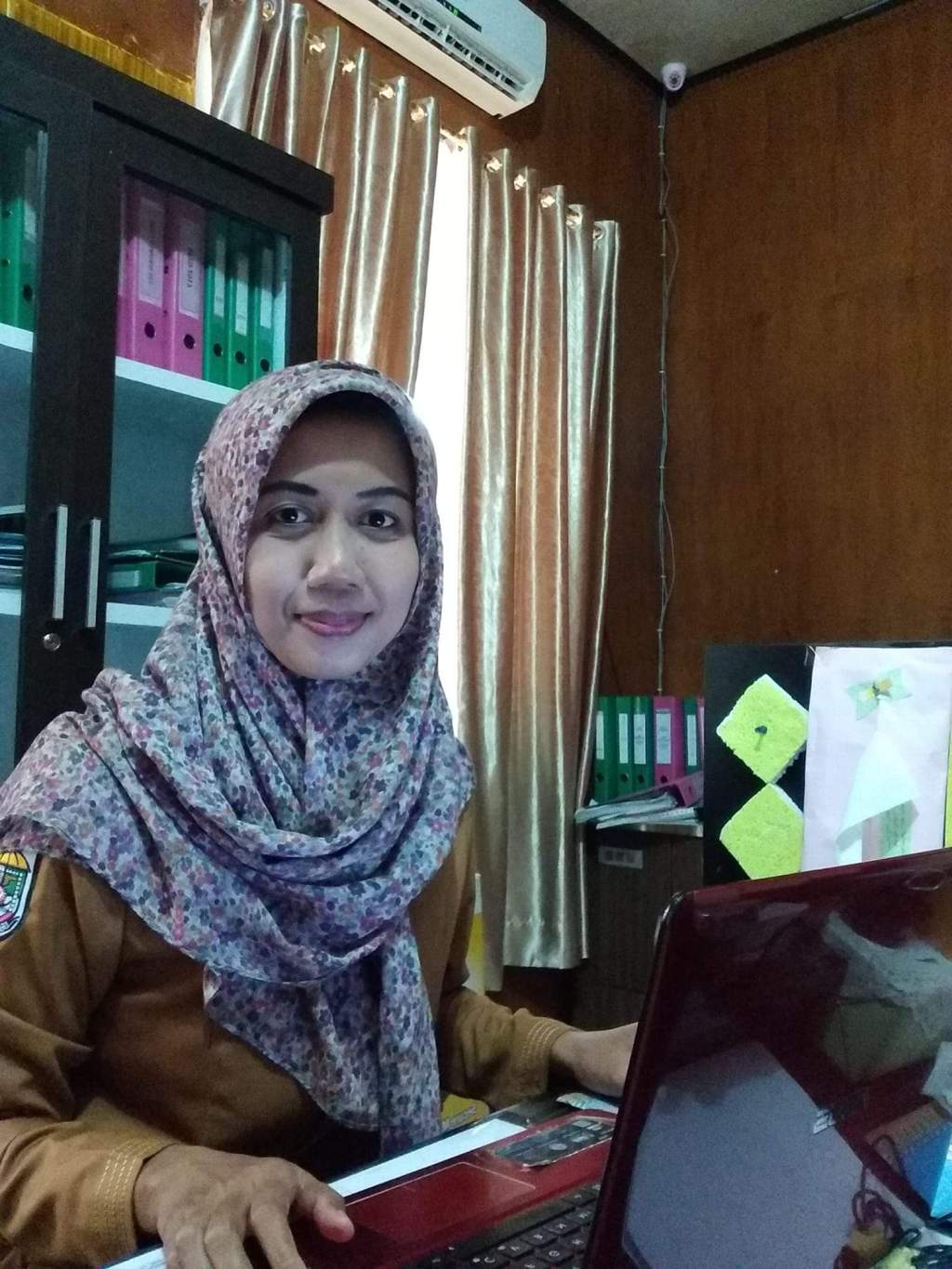Author : Puan Seruni
Saat masih sangat aktif menjadi pewara di berbagai acara, saya selalu menyempatkan diri mencatat di buku kecil hal-hal yang menjadi bahan evaluasi saya saat tampil. Tujuannya untuk menghindari hal-hal fatal yang kemungkinan besar terulang. Termasuk penyebutan nama, pangkat dan jabatan orang-orang penting. Ya, hal tersebut menjadi sesuatu yang sensitif bagi sebagian orang. Apalagi nama pasangan, nama orang tua, nama instansi, dan gelar lain yang disandang.
Saya jadi sering bertanya kepada penyelenggara acara tentang siapa saja tokoh yang datang. Kemudian berangsur memberanikan diri menanyakan langsung pada tokoh yang bersangkutan, termasuk gelar dan jabatannya. Ngarep panitia ngasih jawaban cepat dan tepat di tengah waktu yang sibuk adalah hil yang mustahal, kata pelawak Timbul.
Nah, di sinilah pemikiran saya yang cetek dan mata saya yang picek kampungan ini mulai terbelalak. Ketika terjalin komunikasi singkat dengan tokoh-tokoh besar yang hadir itu, saya mendapatkan ilmu baru mengenai tata krama, kerendahan hati, esensi dan eksistensi. Halahh, mentang-mentang udah gak picek langsung ninggi ye ngomongnya 🤣🤣😎
Ada beberapa kejadian yang menyebabkan saya agak protektif dan progresif soal gelar dan jabatan tersebut. Ada sebuah kejadian yang saya anggap lumrah terjadi namun tidak demikian bagi si pemilik nama dan gelar. Waktu gladi bersih, saya membacakan urutan acara satu persatu lengkap dengan nama pengisi acara. Akhir gladi yang dianggap sempurna oleh pemimpin daerah yang memantau, ternyata dianggap kurang oleh seorang tokoh masyarakat. Dengan gagah beliau mendekati saya dan menegur saya dengan bahasa daerah yang tentu saja tidak mengenakkan hati untuk didengar.
Apalah daya, saya hanya sebagai pembawa acara biasa, masih muda pula (uhukk), terpaksa bilang maaf berkali-kali sambil merendah dan tetap menunjukkan wajah penuh penyesalan. Meski berakibat gladi bersih tetap diulang. Bayangkan, cuma karena tidak menyebut gelar haji seseorang, saya dianggap tidak tahu arti menunggu sekian lama waktu buat naik haji. Tidak tahu betapa mahalnya biaya yang dikeluarkan. Tidak tahu betapa resahnya ketika akan diberangkatkan. Tidak tahu betapa emosionalnya momen melontar jumroh, menghancurkan setan-setan yang berdiri mengangkang. Akibatnya, pulang saya pun jadi kesorean. Yaa.. maklum juga sih saya. Saya yang masih polos dan kinyis–kinyis masa itu lebih memaknai arti sebuah kepastian dalam penantian kapan sih bisa punya pacar? #ngiris2bawang
Efek protes gelar itu pun merembet ke beberapa acara berikutnya. Ada ibu-ibu yang merasa dirinya gak berarti apa-apa saat saya lupa memanggil nama depannya dengan hajjah. Ada yang tidak terima gelarnya tidak dibacakan kepanjangannya. Ada bahkan yang belum wisuda, ngotot minta dibacakan gelar sarjananya. Sambil ngomel mengatakan dia sudah sidang dan menceritakan betapa bertungkus lumusnya dia selama ini bolak-balik ke Pekanbaru demi mengikuti perkuliahan. Ada yang pengen banget dibilang sedang melanjutkan pendidikan S2 di luar kota. Oke sip! Awak ni ikut ajalah. Yang penting hati orang senang. Beginilah nasib seorang kuah sate, saya pikir.
Tapi ada kejadian pembanding yang menyejukkan hati di kemudian hari saat saya didaulat kembali menjadi pembawa acara yang skalanya lebih besar. Menghadirkan beberapa narasumber dari sebuah intansi selevel kementerian. Saat gladi bersih berjalan dengan baik, narasumber tersebut sayangnya belum hadir. Panitia meyakinkan saya nama dan gelar yang tercantum sudah benar. Saya pun menjalankan tugas keesokan hari tanpa beban. Alhamdulillah, acara inti selesai dan berganti dengan sesi penyampaian materi atau ekspose. Nah, karena suasana sudah lebih santai beberapa narasumber yang di acara inti hanya memperkenalkan diri, mulai bisa diajak ngobrol meski tak lebih dari sekedar menawarkan microphone, beberapa ATK yang dibutuhkan atau sekedar mempersilakan mereka menyantap cemilan yang ada. Saat beberapa narasumber memberikan kartu nama usai mengenalkan diri secara pribadi dan ngobrol ringan di meja tunggu. Saya terperangah. Loh, ternyata Bapak ini udah Doktor? Lulusan Jerman pula. Dih, Bapak ini juga setingkat doktor. Gelarnya juga seabreg, ada Eng Ing Eng di belakang namanya. Adalagi yang sudah haji, tapi gak sewot waktu cuma dipanggil namanya saja. Fiuuhh, saya merasa bersalah banget, mungkin faktor trauma juga. Akhirnya saya menghampiri mereka satu persatu usai mereka tampil. “Bapak, saya mohon maaf saya tadi tidak menyebutkan gelar Doktor Bapak..”
Jawabannya sungguh di luar dugaan, selain sikap hangat dan ramah yang menyamankan hati. “Oh, ga masalah Mbak. Cuma gelar aja kok, gak perlu repot minta maaf karena ga disebutkan…” “Hah? Tapi kan Bapak kuliahnya di Jerman, pasti susah meraih gelar itu Pak” “Hehehe, Alhamdulillah saya disekolahkan pemerintah, gak susah-susah amat kok, apalagi harus sampe nunjukkin bahwa saya bergelar Doktor ke semua orang. Santuy aja Mbak,” kata si Bapak sambil senyum, ramaaah banget. Masya Allah… Adem ga sih, dengernya? Ngenyess banget di hati.
Saya kemudian menghampiri narasumber yang bergelar haji. Kata-kata yang sama, memohon maaf atas tidak disebutkannya gelar mulia itu di depan nama beliau sebelumnya. “Eh lah si Mbak MC ini, gak bakal keluar saya dari Islam kalo gak disebutin haji saya Mbak. Hehehe, biar gelar itu Allah aja yang ngasih, lebih panteslah, karena yang memudahkan rezeki saya buat kesana (tanah suci) juga Dia kan?”

Saya tarik nafas panjang. Merasakan kesejukan masuk kerongga dada. Lebay? Biarin. Entah siapa juga yang lebay sebenarnya disini. Huh…
Seperti sebuah arisan, (ada analogi yang lebih pantes gak?) takdir baik saya bertemu dengan orang-orang yang baik pun berkelanjutan. Tidak sekedar baik tapi memiliki ilmu dan budi pekerti yang lebih dan pantas dijadikan tauladan. Salah satunya dengan pegawai negeri dari salah satu daerah di Jawa. Kalau dilihat dari gayanya dibandingkan kebanyakan pegawai honorer di daerah kami, itu Bapak sama Mbak-mbak gak akan sepadan. Maaf, dari kualitas bahan seragamnya saja sudah beda.
Tapi, hidup kan gak terlihat sedangkal itu, Soraya Montenegro!
Saat bertemu mereka, dari gesture-nya saja sudah kelihatan mereka bukan orang sembarangan. Golongan manusia berbobot yang membungkuk-bungkuk bertemu yang lebih tua serta tetap bersikap santun pada yang sebaya dan yang lebih muda. Semua itu semakin terlihat saat mereka berbicara, menyiapkan bahan yang dibutuhkan dan menjelaskan dengan bahasa yang mudah dipahami. Maka apa yang mereka kenakan tak lebih dari sekedar pelengkap saja. Ada sisi yang lebih bernilai untuk dilihat lebih dekat. Perpaduan ilmu yang tinggi, sikap yang rendah hati dan luhurnya budi pekerti. Apalah arti seragam bagus kami yang modis dan berbordir sana-sini di hadapan itu semua? Mereka juga cuma pake ransel sederhana, bukan tas jinjing ber-merk yang mahal, mengkilat dan penuh prestise. Tapi kehadiran mereka yang ternyata sebagian besar lulusan terbaik universitas negeri terkenal di Jawa itu membuat hadirin terperangah, tergerak, terinspirasi bahkan sampai terkesan mendalam itu memberikan tempat tersendiri yang jauh lebih tinggi dari sekedar apa itu yang di namakan dengan prestisius.
Ah, jadi ingat juga dengan para penulis hebat yang pernah saya kagumi dan pernah saya temui. Tak ada kesombongan saat saya mengapresiasi karya-karya mereka yang luar biasa. Salah seorang penulis itu bahkan sering mendapatkan penghargaan sebagai penulis skenario terbaik pada berbagai ajang festival film bergengsi di tanah air. “Kebetulan dapat aja itu Mbak. Ga pernah kepikiran juga sampai harus dapat penghargaan. Biasa aja. Namanya kita kerja sesuai yang diminta ya ngalir aja..” Beliaupun enggan bercerita ketika ditanyakan berapa banyak penghargaan yang telah berhasil diraihnya. Justru lebih antusias menceritakan proses kreatif lahirnya karya-karya itu dan juga bercerita tentang kehidupan sehari-harinya. Keren ga sih? Aku sih yess..
Betapa bersyukurnya saya diperkenankan bertemu dengan golongan orang-orang yang sudah selesai dengan urusan remeh temeh sebuah eksistensi. Orang-orang terpelajar yang sederhana tapi luar biasa sikapnya. Mereka yang lebih mementingkan esensi kehadiran mereka sebagai apa dan membawa manfaat apa bagi sesama, bukan mengenakan apa dan terlihat seberapa gimana dimata sesama. Orang-orang yang bener melaksanakan apa yang dikatakan oleh filsuf Jean Paul Satre, “tugas eksistensialis manusia adalah memberi esensi pada kehidupannya.” Mereka yang selesai dengan dirinya itu kemudian membuat saya bertanya sendiri. Bagaimana dengan saya ya? Apa pantes saya yang masih ngos-ngosan untuk bisa lanjut kuliah, terus diburu cicilan bulanan dan sangat complicated ketika berhadapan dengan urusan kebutuhan hidup yang begitu sophisticated ini (halah apasik), tetep kekeuh mengutamakan eksistensi agar bisa tetap dipandang dan diakui? Dipandang sebagai apa? Diakui sebagai apa? Hmmm, sebagai penulis yang baik? Cihh, kalo ga kenal sama yang punya Blog ini, tulisan paling juga ngetem lama di konsep. (Nyuwun ngapuro nggih, Romo 🙏🙏). Paling banter di-posting di Facebook. Kena like atau love, cuma karena temen baik aja, itu pun pada males mbacanya. Yaa, daripada enggak kasih lah. Fiuhh…membatin sendiri aja sudah segini perih kata-katanya. Apalagi kalo orang yang ngomong..
Jadi dipandang dan diakui sebagai apa dong? Entahlah, malu! Nah kan, malu sendiri kan jadinya? Mengingatkan saya pada sebuah puisi karya Taufik Ismail yang berjudul;
Kerendahan Hati
Kalau engkau tak mampu menjadi beringin yang tegak di puncak bukit
Jadilah belukar, tetapi belukar yang baik,
Yang tumbuh di tepi danau
Kalau kamu tak sanggup menjadi belukar,
Jadilah saja rumput, tetapi rumput yang
Memperkuat tanggul pinggiran jalan
Kalau engkau tak mampu menjadi jalan raya, Jadilah saja jalan kecil,
Tetapi jalan setapak yang
Membawa orang ke mata air
Tidaklah semua menjadi kapten
Tentu harus ada awak kapalnya
Bukan besar kecilnya tugas yang menjadikan tinggi
Rendahnya nilai dirimu
Jadilah saja dirimu
Sebaik-baiknya dari dirimu sendiri.
Duhai, betapa level tertinggi yang seharusnya dijangkau manusia dalam hidup ini tetaplah sebuah kerendahan hati.