Author : Herman Attaqi
Sarip, dalam kisah Tambak Oso yang terkenal di daerah Jawa Timur, adalah seorang pemuda jagoan kampung yang terkenal keras kepada government Hindia Belanda. Ia juga kerap merampok harta milik para saudagar kikir dan lintah darat untuk dibagi-bagikan kepada orang-orang miskin. Sarip juga sangat hormat dan sayang kepada Ibunya. Pernah suatu kali ia balik menghajar Lurah Gedangan karena si Lurah telah semena-mena menghajar Ibunya. Sarip, sang bengal baik hati ini akhirnya mati dihajar Paidi, jagoan dari Kulon Kali dan mayatnya dibuang ke Sungai Sedati.
Tapi, Ibunya yang tengah mencuci di Sungai Sedati terkejut setelah menelusuri jejak warna merah di aliran sungai ternyata mayat anaknya. Mboke Sarip langsung berteriak, “Sariiip.. durung wayahe, Nak.” (Sariiip.. belum waktunya, Nak). Ajaib. Sarip langsung bangkit dari kematian dan berlari memeluk Ibunya seolah-olah tidak terjadi apa-apa.
Di ranah Minang Kabau, Sumatera Barat, kita mengenal legenda Malin Kundang. Seorang anak durhaka yang malu mengakui Ibu yang miskin. Lalu, Ibunya murka dan mengutuk Malin Kundang menjadi batu. Kita juga mengenal jejak legenda yang mirip di beberapa tempat seperti Joko Budeg di Tulung Agung. Juga Sangkuriang dari tanah Pasundan. Semuanya mengisahkan tentang tuah atau kesaktian seorang Ibu terhadap anaknya. Betapa sebagai sebuah legenda yang lahir dari kearifan yang hidup dalam pikiran anak manusia, Ibu ditempatkan sebagai pusat kehendak atas kebaikan dan keburukan, bahkan kehidupan dan kematian.
Leo Tolstoy, dalam novel Haji Murat, menceritakan dengan tragis tentang Haji Murat, seorang pejuang bangsa Chechnya yang gagah berani melawan penjajahan bangsa Rusia di bawah Tsar Nikolai I, pada akhirnya lebih memutuskan, bahwa berperang demi membebaskan Ibunya, Patimat beserta isteri dan kelima anak-anaknya jauh lebih penting dari pada berjuang untuk membela tanah air. Ibu, bagi Haji Murat lebih menentukan pondasi nilainya dari pada hal-hal yang lain, meski akhirnya ia tetap gagal dan mati. Tapi, kekalahan adalah soal lain. Mau bagaimana lagi? A la guerre comme a la guerre. Namanya saja perang. Cuma ada dua moralitas yang tersisa, membunuh atau dibunuh.
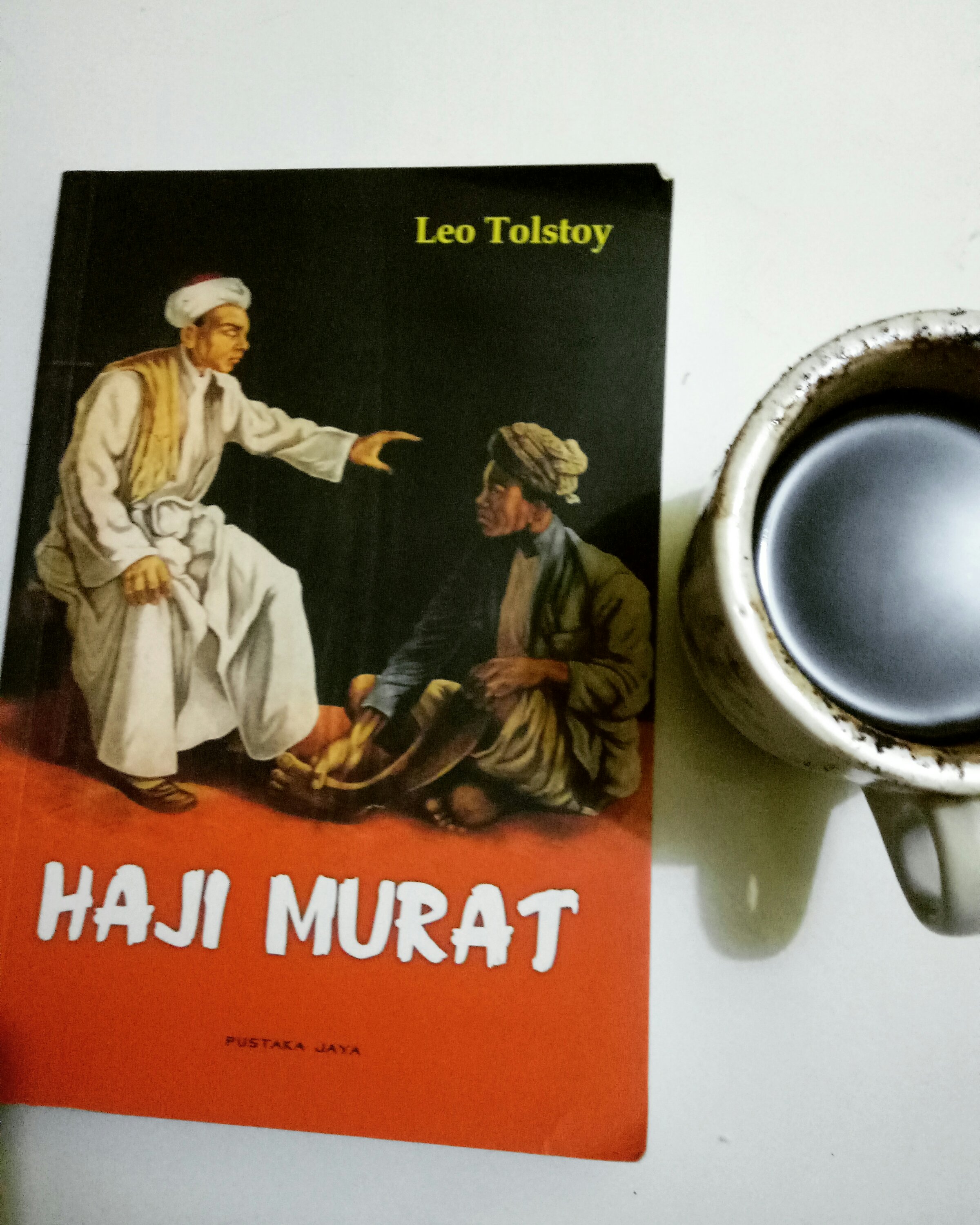
Dalam keseharian pun kita sering menempatkan nilai etis, “bagaimana jika hal itu juga terjadi pada Ibumu?” kepada sesuatu/seseorang yang melecehkan/merendahkan perempuan. Meski hal itu belum lah cukup dijadikan landasan yang kuat, tapi yang jelas Ibu menjadi pokok pangkal etika sekaligus menggugat nurani paling dasar manusia tentang bagaimana memandang perempuan. Sepertinya pertanyaan ini juga bisa dijadikan sebuah komentar beberapa postingan (sepertinya diposting oleh para lelaki) dari utas berita yang banyak seliweran beberapa waktu yang lalu di postingan facebook tentang peraturan pemerintah yang mewajibkan lelaki Aljazair untuk ber-poligami. “Bagaimana jika Ibumu yang dimadu?” Sebuah sinisme, memang. Meski bisa jadi postingan itu hanya bermaksud gurauan belaka. Iya. Apa ndak ada bahan gurauan lagi selain itu? Poinnya, meski hal itu terdapat dalam ajaran Islam, tak mesti juga dijadikan bahan candaan maskulinitas. Banal sekali kesannya. Cukuplah dia dibicarakan oleh ulama yang mumpuni keilmuannya. Dan, saya pun tak hendak memperdebatkan itu.
Saya pernah berjanji kepada seorang kawan akan menulis esai tentang seksisme, janji yang sudah begitu lama. Kawan itu pun sepertinya sudah lupa dengan janji tersebut. Apakah karena menulis tentang perempuan itu susah? Uhh, ini juga bisa jadi pertanyaan yang berbahaya. Kita sering terjebak pada pikiran bias gender seperti ini. Tapi, yang saya sadari sekarang adalah ternyata selama ini saya lebih mudah membaca buku-buku yang ditulis oleh penulis laki-laki, seperti Sigmund Freud bahkan Karl Marx, Eka Kurniawan atau pun Pramoedya Ananta Toer.
Suatu ketika, saya ditanya tentang siapa sastrawan favorit saya, spontan saya jawab Ernest Hemingway, penulis The Old Man and the Sea. Siapa penyair Indonesia yang terbayang di kepala? Sitor Situmorang. Lelaki lagi, tho. Tentunya dengan tidak menampik beberapa buku yang ditulis oleh penulis perempuan, seperti Leyla S Chudori, eh, siapa lagi, ya?
Fathimah Fildzah Izzati dalam esainya di Indoprogress.com yang berjudul Feminisme dan Imaji Pembebasan Perempuan dalam Kapitalisme, mengutip Fay Weldon dalam buku One Dimensional Man yang ditulis Herbert Marcuse mengatakan, “What makes women happy? Ask them and they’ll reply, in roughly disorder : sex, food, friends, family, shopping, chocolate.” Apa yang membuat perempuan bahagia? Tanyakan pada mereka dan mereka akan menjawab, secara tidak berurutan : seks, makanan, teman, keluarga, belanja, coklat. Akibatnya, kata Fathimah, imaji mengenai perempuan yang bebas dan berbahagia yang ditampilkan secara terus menerus melalui iklan menjadi imaji ‘umum’ yang diterima sebagai sebuah hal yang wajar.
Mungkin begitulah gambaran umum dekonstruksi pemikiran tentang perempuan. Sepertinya kita patut mencurigai sebuah upaya yang massif melanggengkan struktur patriarki yang makin dominan. Melihat perempuan dari persepsi yang seolah-olah menjadi laku yang feminis, padahal sebenarnya perempuan justru dijadikan objek bagi konsumerisme, hasrat mengeruk untung kapitalisme. Mereka hanya dilirik sebagai pasar yang menggiurkan bagi obat pelangsing, kosmetik kecantikan dan segala tetek bengek produk yang tujuannya dalam rangka ‘membuat suami betah di rumah’ dan, sayangnya, perempuan hanya sekedar obyek.
Lalu, apa kaitannya pandangan seksis tersebut dengan kisah-kisah Tambak Oso, Malin Kundang, Joko Budeg, Sangkuriang bahkan juga Haji Murat di atas? Balik lagi ke ‘Ibu’ sebagai pusat etik dan titik pangkal kebaikan dan keburukan. Ibu, sebagai perempuan, memiliki legitimasi moral yang cukup potensial jika berhadapan dengan pandangan seksis dan bias gender kaum lelaki. Kisah-kisah yang tumbuh dari kenyataan sosial memberikan gambaran nyata bahwa nilai ‘ke-Ibu-an’ sesungguhnya bisa dieksplorasi lebih dalam lagi, serta dipraktekkan dalam laku sosial kita. Lewat pertanyaan, “bagaimana jika itu Ibumu?” bisa dijadikan sebagai pintu masuk. Meski pun saya sadari hal itu masih jauh dari kata selesai. Tapi, ia minimal membuka sebuah jalan untuk mengkonstruksikan sebuah kesadaran kolektif kita berkenaan dengan isu-isu gender yang lebih konkrit dan materil. Bukankah sebuah ide tidak boleh terlalu jauh meninggalkan basic materinya?
Dalam perspektif yang lain, bisa juga seorang Ibu berperan sebagai objek yang berubah karena nilai yang dibangun oleh anaknya. Maxim Gorki dalam novel Ibunda menceritakan dengan sangat indah dan natural bagaimana Pelagia, Ibunda dari anaknya Pavel yang setiap hari melakukan konsolidasi dan rapat-rapat politik bersama kawan-kawannya di rumah untuk menggalang sebuah perlawanan kaum buruh dan tani terhadap penindasan yang dilakukan oleh pemilik modal dan tuan tanah.
Pelagia, bertransformasi dari seorang yang ketakutan dan tertindas terutama oleh suaminya, kemudian menjadi aktifis yang terjun ke medan perlawanan sebagai pendistribusi pamflet. Semangat perlawanannya makin berkobar ketika anaknya, Pavel, dipenjara dan diasingkan ke daerah terpencil di Siberia.
Inilah akhir kisah Pelagia saat bertubi-tubi pukulan didaratkan ke sekujur tubuhnya. Dan, Ibunda berteriak untuk penghabisan sebelum tangan polisi militer mencekik lehernya, “bahkan samudera darah pun tak kan mampu tenggelamkan kebenaran.”
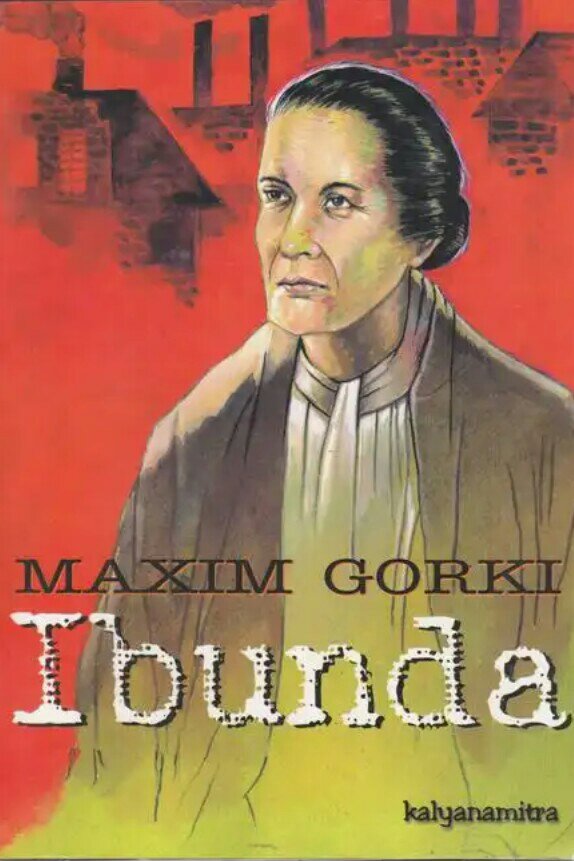
Seorang Ibu tetaplah seorang Ibu. Muara bagi cinta yang utuh. Dalam hidupnya, ia mengajarkan kasih sayang bahkan ketabahan. Dalam kematian, ia menumbuhkan kerinduan dan kehangatan. Saya pun teringat almarhumah Omak, Ibunda yang telah lebih dulu meninggal dunia. Seringkali kerinduan saya padanya menggerakkan hati untuk mengikuti kebiasannya membaca surat yasin sebagai amalan hari-hari semasa hidup beliau. Ada dorongan kebaikan, di antara banyak hal tentangnya yang tetap akan saya peluk dalam ingatan, bersebab berharap untuk kebaikannya. Ada doa yang harus dikirim sebagai hadiah padanya. Ada banyak yang tak terkatakan tentang Omak dan pastinya akan tetap bersedekap di lengan dan dada ini. Seorang Ibu, bahkan setelah kematiannya masih pula hidup dan menghidupkan pengalaman beserta dorongan kebaikan lainnya.
Secara kolektif, kita memang membutuhkan satu nilai yang mengikat pengalaman kita secara kuat, seperti pengalaman seorang anak pada Ibunya. Isu-isu perempuan harus digali lebih dalam sebagai landasan etik kita dalam lingkup psiko-sosiologis. Seperti manusia sebagai individu, manusia secara komunal memang membutuhkan sosok ‘Ibu’ sebagai sumber moralitas yang kuat dan mengikat. Bukan saja oleh sebuah kesepakatan politis, tapi yang jauh lebih penting, adalah oleh pengalaman psikologis. Ini, barangkali, sebuah tawaran dari upaya menggali dan mencari nilai etis bagi peradaban dunia yang limbung dan goyah. Menemukan titik temu dari bentrokan ideologi yang tak berkesudahan. Ah, saya terlalu berlebihan. Lebay! Biarin dah.
Jika manusia masih memiliki sosok Ibu, dunia akan tetap memeluknya penuh kehangatan.***
