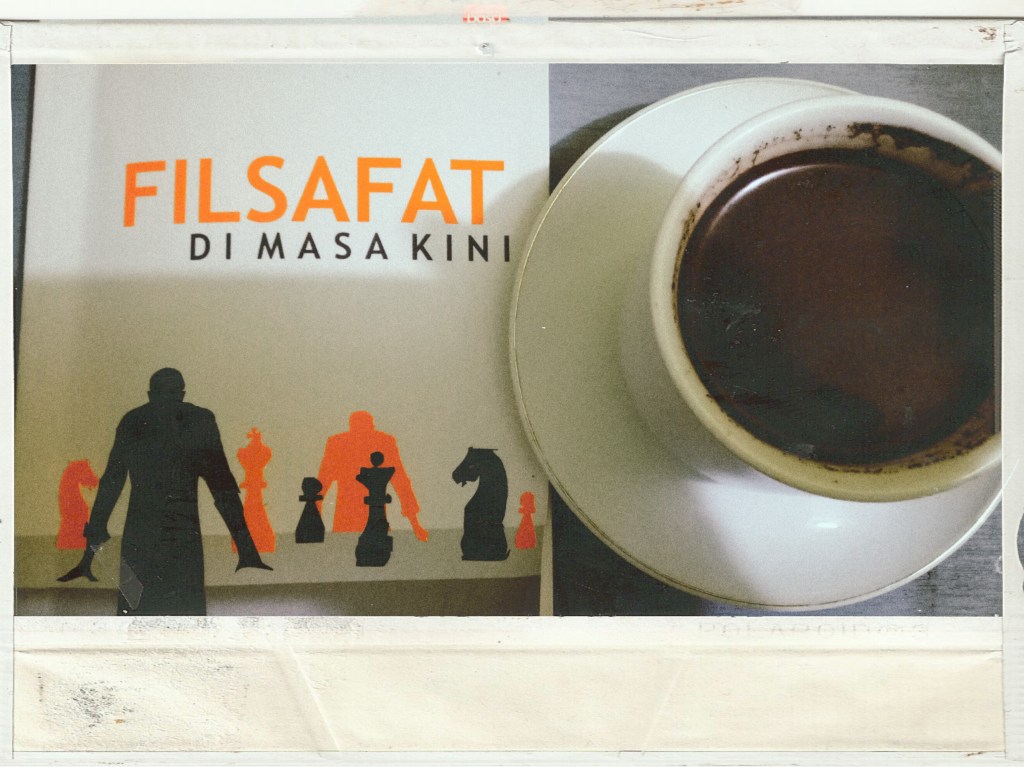“Apakah filsuf harus ambil bagian dalam peristiwa-peristiwa kontemporer dan mengomentari semua hal?”
Oleh Herman Attaqi
Membaca sekaligus me-review buku dalam mengawali tahun 2020 ini sepertinya akan menyenangkan. Bukan buku baru, sih. Di awal tahun ini akhirnya saya bisa menuntaskan membaca buku ini untuk ke dua kalinya. Penerbit BASABASI dari Yogyakarta menerbitkannya sebagai buku terjemahan yang berjudul “Filsafat Di Masa Kini” yang diterjemahkan oleh Noor Cholis dengan penyunting Tia Setiadi.
Ide penulisan buku ini berawal dari sebuah diskusi publik yang diprakarsai oleh Francois Laquieze, mantan direktur Institut Kebudayaan Prancis di Wina, yang mengundang duo filsuf kondang Alain Badiou dan Slavoj Zizek. Kemudian melalui suntingan oleh Peter Engelmann jadilah manuskrip hasil diskusi itu sebagai sebuah buku yang tengah saya review ini.
Awalnya saya mengira akan mendapati konfrontasi pemikiran yang ekstrem dari dua filsuf paling mentereng zaman kiwari. Namun anggapan saya keliru, karena keduanya justru menyatakan bersepakat dalam banyak hal. Seperti ungkapan pamungkas Zizek di akhir diskusi, “dengan Badiou, di lain pihak, saya merasa — seperti kata Ribentrop kepada Molotov dalam perjalanannya ke Moskwa pada 1939 — ‘sesama kamerad.’”
Apa yang membuat mereka — Badiou dan Zizek — bersependapat dalam diskusi ini? Mari simak komentar Badiou, “untungnya, di sini kami berbicara tentang komitmen dan konsekuensi filsafat, bukan tentang organisasi konsep-konsepnya. Sehingga kesepahaman kami lebih besar karena kami belum benar-benar memasuki konstruksi filosofis itu sendiri.”
Jadi, menariknya buku ini di mana?
Justru di poin itulah buku setebal 136 halaman ini menjadi menarik. Dengan pertanyaan yang menjiwai buku ini, “apakah filsuf harus ambil bagian dalam peristiwa-peristiwa kontemporer dan mengomentari semua hal?”, membawa diskusi ini menjadi lebih relevan terkait cara pandang kita melihat hubungan filsafat (juga filsuf) dengan realitas.
Hmm~
Padahal pertama kali saya secara akademik mempelajari filsafat, dengan hiperbolik, saya telah mengira bahwa filsafat itu adalah usaha untuk menafsirkan sekaligus mengubah dunia. Badiou dan Zizek malah “hanya” bicara tentang apakah filsafat itu mesti ambil bagian dalam peristiwa kontemporer? Bayangkan, dari menafsir dan mengubah, peran filsafat diperkecil lagi oleh duo maut ini menjadi terlibat atau tidak.
‘Situasi Filosofis’ Alain Badiou
Alain Badiou mengatakan bahwa ide seorang filsuf bisa berbicara tentang apa saja yang kemudian dimanifestikan oleh “filsuf TV” adalah ide sesat. Wait, sesat? (Sambil membayangkan Rocky Gerung di ILC TvOne) Mengapa bisa gitu, pak Badiou?
Karena filsuf mengonstruksi problem-problemnya sendiri, dialah pencipta problem, itu artinya dia bukanlah orang yang bisa ditanya-tanya di televisi tentang segala macam kejadian. Seorang filsuf itu, kata Badiou, adalah seseorang yang menyodorkan problem-problem baru. Artinya filsafat, pertama dan terutama, adalah tentang penciptaan problem-problem baru.
Filsafat sebagai pencipta problem baru?
Artinya ketika filsuf terlibat dalam situasi — entah itu historis, politis, artistik, asmara, ilmiah … — ia melihat itu semua sebagai isyarat bahwa perlu diciptakan problem baru. Dalam kondisi apa dan bagaimana seorang filsuf bisa melihat isyarat-isyarat bagi sebuah problem baru itu? Dalam kerangka berpikir demikianlah Badiou memperkenalkan ungkapan yang disebutnya sebagai “situasi filosofis”. Bahwa tidak semua kejadian di dunia ini adalah situasi bagi filsafat atau situasi filosofis.
Di dalam buku edisi cetakan pertama Desember 2018 ini, Badiou menjelaskan tentang tiga buah situasi filosofis dengan pengantar tiga buah cerita (Silahkan dibaca sendiri cerita-ceritanya di buku tersebut). Apa saja tiga situasi filosofis yang menjadi dasar bagi filsafat bisa ikut terlibat di dalam problem masyarakat?
Pertama; sebuah situasi filosofis terdapat dalam suatu momen ketika sebuah pilihan (harus) dijelaskan. Baik itu sebuah pilihan eksistensi maupun sebuah pilihan pemikiran.
Jadi boleh dong seorang filsuf, ehm, Rocky Gerung mengomentari tentang Pemilu, umpamanya?
Boleh saja. Akan tetapi ketika para filsuf menawarkan pandangannya tentang masalah tersebut, dia adalah seorang masyarakat biasa, tidak lebih: dia tidak berbicara dari sebuah posisi konsistensi filosofis tulen.
Kok bisa gitu?
Pada dasarnya dalam fungsi sederhananya, demokrasi elektoral, baik pemenang ataupun yang kalah; mayoritas atau oposisi memiliki ukuran standar yang sama. Artinya tidak ada hubungan paradoks di antara keduanya. Mereka memiliki perbedaan tentu saja. Tapi perbedaan dalam taraf itu hanyalah perbedaan biasa yang masih berada dalam satu lingkup sistem politik yang reguler. Tidak ada sejatinya hubungan paradoks yang memungkinkan adanya isyarat bagi situasi filosofis. Karena cepat atau lambat, oposisi bisa saja menggantikan mayoritas dan begitu sebaliknya.
Oke. Situasi filosofis yang kedua?
Kedua; sebuah situasi filosofis terdapat dalam upaya menjelaskan jarak antara kekuasaan dan kebenaran.
Ada sebuah contoh selama pendudukan tentara Amerika Serikat di pinggiran kota Wina, pada akhir Perang Dunia Kedua, seorang prajurit membunuh, jelas tanpa mengetahui siapa yang dibunuhnya, seorang genius musik terbesar masa itu, komponis Anton Webern.
Kejadian tersebut adalah sebuah isyarat adanya situasi filosofis yang harus dijelaskan akibat dari ketegangan yang terjadi karena adanya jarak antara kekuasaan dan kebenaran. Sebuah kecelakaan yang kemudian membawa ke situasi filosofis aksidental.
Trus, situasi filosofis yang ketiga?
Ketiga; situasi filosofis terdapat ketika kita memikirkan perkecualian dari peristiwa. Kita harus mengetahui apa yang harus kita katakan tentang apa yang tidak biasa. Kita harus memikirkan transformasi kehidupan.
Pada situasi filosofis yang ketiga ini, Badiou menggambarkan sebuah adegan film atas sebuah hubungan percintaan yang rumit, yang melawan norma sosial, hukum, dan kelindan hasil dari pilihan-pilihan manusia yang saling tumpang tindih, yang melahirkan sebuah isyarat bagi situasi filosofis.
Apa yang harus dikatakan oleh filsafat dalam situasi ini? Kita harus memikirkan peristiwa. Memikirkan perkecualian. Mengetahui tentang hal yang tak biasa. Memikirkan tentang transformasi kehidupan.
Pak Badiou, bisakah saya menyimpulkan bahwa dari analisa yang bapak sampaikan di atas ada tiga situasi filosofis, yakni pilihan, jarak dan perkecualian, yang jika dengan tiga situasi itu kita bisa memahami filsafat sebagai sesuatu yang bisa mengubah eksistensi?
Ya. Betul, Bung. Bisa diterjemahkan begitu.
Bagi Zizek, Filsafat Bukanlah Sebuah Dialog
Sebagaimana yang kita ketahui bahwa Zizek dan Badiou sudah lama saling berteman baik, meskipun mereka tidak sepaham dalam berbagai konsep dan pengertian-pengertian filosofis yang penting. Badiou banyak menerjemahkan karya Zizek ke dalam bahasa Prancis. Begitupun Zizek adalah tukang review dan pengkritik pemikiran dan karya Badiou yang intens.
Tapi dalam diskusi di buku ini, mereka memiliki kesepemahaman bahwa keterlibatan filosofis harus dihasilkan dari spesifikasi pemikiran filosofis dan harus juga menetapkan batas-batasnya dalam pengertian ini.
Wow~
Seperti biasa, Zizek adalah filsuf yang tajam sekaligus kocak. Ia mengawali pidatonya dengan sebuah ungkapan bahwa filsafat bukan sebuah dialog. Ilustrasinya begini, jika seorang sedang duduk di kafe dan seseorang lainnya menantang, “ayo, kita bahas itu secara mendalam!” Seseorang yang benar-benar filsuf akan mengatakan, “maafkan saya, saya harus pergi,” dan memastikan dia menghilang secepat mungkin.
Dan jika dalam diskusi ini hampir tidak terjadi dialog antara saya, kata Zizek, dengan Badiou karena terlalu banyak kesepahaman antara kami, mungkinkah itu adalah sebuah tanda filsafat riil?
Hehe~
Zizek mengatakan bahwa yang diperlukan saat ini adalah mengubah konsep perdebatan.
Maksudnya?
Begini. Jika seseorang menanyakan sesuatu kepada kami para filsuf, misalnya: saat ini kita sedang berperang melawan teror, dan itu menyodori kita problem yang menciutkan hati, apakah kita harus menukar kebebasan kita dengan keamanan dari teror? Apakah kita harus membawa keterbukaan liberal ke titik ekstrem — sekalipun jika itu berarti memenggal akar kita dan kehilangan identitas kita — atau haruskah kita menegaskan identitas kita lebih kuat lagi? Menunjukkan bahwa alternatif-alternatif yang kita hadapi secara kolektif membentuk “sintesis-disjungtif”, artinya semua alternatif itu palsu belaka. Dan hal ini haruslah menjadi isyarat bagi para filsuf: dia harus mengubah konsep perdebatan itu sendiri.
Konkretnya apa ini, Om Zizek?
Dalam kasus kita, konkretnya, itu artinya istilah “liberalisme”, “perang melawan teror” dan apa yang disebut “terorisme fundamentalis”, semuanya adalah sintesis disjungtif, palsu belaka. Konsep perdebatan seperti ini yang harus diubah.
Di dalam buku ini Zizek juga mengkritisi banyak hal yang terkait dengan “konsep perdebatan yang harus diubah” ataupun sesuatu yang sintesis disjungtif itu. Di antaranya; Zizek menelaah aksi para filsuf besar Eropa seperti Derrida dan Habermas, tentang realitas virtual, konsep hedonisme, New Age, bahkan Zizek juga mencemooh pemikiran Dialektika Pencerahaan-nya Adorno dan mazhab Frankfurt, hingga neo-Kantianisme.
Ngeriiii memang Om Zizek ini..
Ya, iyalah.
Kembali ke pertanyaan awal, lantas apakah peran filsafat itu menurut Om Zizek?
Di sini kita menghadapi sebuah paradoks: filsafat hampir tidak pernah, dan setidak-tidaknya dalam periode-periode kreatifnya, memainkan sebuah peran normal dalam arti ia hanyalah filsafat saja.
Contohnya?
Pada abad ke-19, kesusasteraan di beberapa bangsa, seperti Hongaria dan Polandia, sering memainkan peran filsafat; misalnya, visi filosofis dan ideologis yang meletakkan fondasi gerakan nasional banyak dirumuskan dalam kesusasteraan.
Akan tetapi, ketika komunisme runtuh (artinya ini adalah sesuatu yang politis), orang justru kembali kepada filsafat untuk merumuskan perlawanannya. Sesuatu yang bersifat lebih politis terjadi dibanding waktu yang lampau.
Tapi di Jerman, filsafat Jerman tak lain hanyalah filsafat. Padahal sejak Heine hingga Marx, kita tahu bahwa filsafat adalah kata pengganti bahasa Jerman untuk revolusi. Dilemanya, dan mungkin kebenarannya, barangkali tidak terlihat revolusi di Jerman adalah syarat bagi filsafat Jerman. Berbeda dengan Prancis yang memiliki situasi revolusionernya sendiri. Inilah dilemanya: Anda tidak bisa memiliki kedua-duanya.
Jadi apa gagasan Om Zizek untuk hal ini?
Barangkali kita harus putus dengan mimpi bahwa ada sebuah filsafat yang normal. Barangkali filsafat adalah abnormalitas par excellent. Karena itu, walau sering berseberangan pemikiran, saya harus selalu membaca teori Badiou.
I see, anything else I should know?
Demikianlah sebagian inti dari diskusi antara Alain Badiou dengan Slavoj Zizek yang oleh Peter Engerlann, sang Editor di dalam catatan pengantar buku ini mengatakan bahwa jawaban-jawaban yang diberikan oleh kedua filsuf ini ternyata lebih sederhana dan lebih skeptis dari yang mungkin diharapkan orang dari para filsuf. Bukannya berlindung pada kejayaan lama yang sudah sejak dulu menjadi kadaluwarsa secara historis, mereka justru mencoba mengingat-ingat kualitas spesifik pemikiran filosofis dan menimba jawaban-jawaban mereka dari situ.
Saya kira, setelah dua kali saya membaca buku ini secara utuh dan mengulang-ulang beberapa kali di bagian tertentu, saya justru melihat kelebihan isinya dari analisis spontan dan tajam dari dua filsuf ini terhadap perkara yang menjadi pertanyaan mendasar banyak orang, termasuk saya pribadi tentang “apa peran filsafat hari ini?”
Sebagai sebuah bacaan, buku ini saya masukkan ke dalam buku penting yang harus saya baca berulangkali. Jikapun ada kelemahannya, mungkin tidak adanya perdebatan ataupun pertentangan yang berarti dari pemikiran dua orang ini. Kelemahan berikutnya, karena buku ini adalah transkrip utuh (sesuai dengan isi diskusi) tanpa dipoles untuk kepentingan penerbitan, kita tidak mendapatkan konsepsi teoritik yang kuat dari kedua gagasan filsuf ini. Sekali lagi, kelemahan itu — pada sisi lainnya — saya dapati sebagai kelebihan.
Sebagai dua filsuf besar, Badiou dan Zizek, adalah dua orang yang ingin saya ajak selfie sembari menulis caption di media sosial seperti perkataan Ribentrop kepada Molotov dalam perjalanannya ke Moskwa pada 1939 — ‘sesama kamerad’.