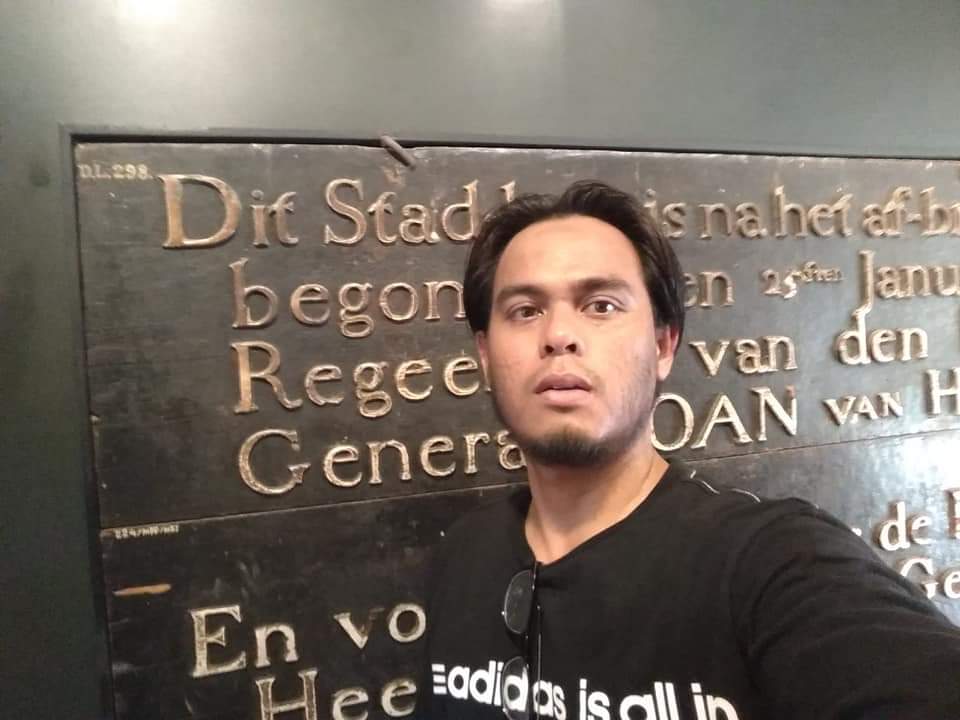“Sebab, manusia jauh lebih celaka kelakuannya daripada mambang paling jahat sekalipun.”
Oleh Panji Prasetya
Ineyah hilang!
Itulah sumber keributan di kampungku dalam dua hari ini. Anak perawan yang hampir cukup umur untuk dikawinkan dalam adat kebiasaan kami itu mendadak raib dari rumah, sebab musababnya pun belum diketahui.
Ineyah beberapa tahun lebih tua dari usiaku, berkulit lebih terang dibandingkan anak gadis lainnya. Dengan rambut panjangnya yang ikal sebahu, di sini, ia dianggap sebagai seorang gadis yang cantik.
Hari masih belum bisa dikatakan pagi, sebab matahari belum sempurna menampakkan terang, ketika tiba-tiba terdengar ketukan tergesa-gesa dari balik pintu rumahku. Ibuku yang sedang berada di belakang, datang setengah berlari melintasi ruang tengah menuju sumber suara. Kudengar pintu dibuka, dan suara pak Maradi tetangga jauhku memberondong dengan pertanyaan apakah Ibuku mengetahui keberadaan Ineyah anaknya. Sebab beberapa minggu yang lalu, anak gadisnya itu sering mengunjungi Ibuku saat siang hingga petang hari. Kata Ibuku, Ineyah minta diajari rupa-rupa keahlian yang sudah seharusnya dimiliki setiap perempuan menjelang dewasa. Terlebih Ineyah tiada lagi memiliki Ibu, sehingga ia bertandang ke rumahku untuk belajar dari Ibu.
Ibu meyakinkan pak Maradi, kalau ia belum bertemu Ineyah lagi sejak dua hari yang lalu. Suara pak Maradi terdengar sungguh cemas. Katanya, sudah beberapa tetangga yang ia datangi, namun hasilnya sama, tak ada yang melihat keberadaan anak gadisnya itu.
Pak Maradi menjelaskan kalau tadi malam Ineyah masuk ke kamarnya seperti biasa. Namun, ia tak kunjung keluar kamar untuk mengerjakan pekerjaan rutinnya di dapur, yakni menyiapkan makanan untuk pak Maradi dan adik-adiknya, sebab pak Maradi tinggal bersama anak-anaknya yang lain.
Desas-desuspun menguar bagai asap tebal yang menyebar dengan cepat di musim kemarau. Saat pagi ketika para perempuan dewasa berkumpul di bawah pohon rindang di dekat rumah salah seorang dari mereka, beberapa di antaranya berbisik, meski cukup keras untuk didengar oleh yang lain. Memulai percikan cerita yang dibumbui tambahan cerita yang menakutkan untuk didengar bahkan oleh orang dewasa sekalipun. Hampir semuanya berbicara dalam kerumunan itu, dan gemuruhnya membuat sebagian cerita itu singgah di telingaku.
Dahulu sewaktu aku masih bayi, ada kejadian aneh yang menimpa salah seorang suami malang dari wanita yang tinggal di dekat muara pulau kecil lainnya, di seberang pulau kampungku. Ketika lelaki itu meninggalkan rumahnya pada sore hari, sang isteri tidak mendapatkan firasat apapun tentang kejadian yang akan menimpa suaminya tersebut. Ia pergi dengan membawa joran pancingnya menaiki perahu kecil menuju muara saat air sedang pasang. Dan hingga malam hari lelaki itu tidak kembali. Saat malam telah gelap sempurna dan bulan meninggalkan malam, isterinya yang merasa cemas kemudian meminta beberapa lelaki dewasa lainnya untuk melihat keadaan suaminya.
Kemudian beritanya benar-benar buruk. Suaminya menghilang! Mereka hanya mendapati perahunya yang tak tertambat, terombang-ambing di dekat semak pepohonan di tepian muara. Selain itu hanya keheningan yang mereka temukan. Suaminya lenyap tak berbekas.
Sebagian menduga pria itu tenggelam dan dibawa arus, akan tetapi hingga hari kedua jasadnya tak pernah muncul ke permukaan. Seorang pemancing lainnya bersaksi bahwa dia sempat melihat keberadaan lelaki itu di balik semak-semak rimbun di dekat muara. Ia mengira lelaki itu turun sebentar untuk menangkap biawak yang terjerat, sebelum kemudian menghilang, lalu samar-samar sosoknya terlihat menyatu dengan kegelapan seperti garam yang melebur di dalam air laut.
Ketika kemudian kabar itu diberitakan kepada isterinya, wanita itu langsung jatuh pingsan. Kenyataan itu begitu mengejutkan. Jantungnya terlonjak menyempitkan pembuluh kesadarannya. Siapa pernah menyangka, seseorang yang dicintai menghilang tanpa jejak di langit malam?
Hingga pada hari ke tujuh berita raibnya, saat hampir seluruh keluarga lelaki itu berkumpul untuk mengadakan pertemuan kerabat, lelaki itu tiba-tiba datang begitu saja kembali ke rumah dalam keadaan linglung seperti ikan yang dikeluarkan dari dalam air. Dan tatapan matanya, seakan tak memikirkan sesuatupun selain terlihat sebagai lelaki yang melamun, dan tatapannya kosong.
Orang-orang segera berhamburan, dan bersuka cita dengan kepulangannya yang tak terduga itu. Tapi, riuh itu memudar berganti keheningan yang dipenuhi tanya yang tak terjawab, ketika lelaki itu hanya diam mematung tak berkata apa-apa, saat isterinya mendekapnya, ia bahkan tak mengenali siapapun di sekelilingnya.
Lelaki lain yang mengantarnya pulang menemukan pria malang itu di dekat batu besar tak jauh dari muara. Semua orang menjadi heran, sebab tak sepetak tanah pun yang tidak mereka sisiri ketika pria itu lenyap begitu saja. Dan kini ia muncul begitu saja bagai hujan yang jatuh tiba-tiba di tengah hari di musim kemarau. Alih-alih hujan itu memberi kesejukan, justru menimbulkan rasa takut akan hadirnya sebentuk bencana lainnya. Lelaki malang itu telah berubah menjadi seorang suami yang linglung.
Orang-orang yang dipandang ahli dalam masalah itu kemudian angkat bicara, meski tak diperlukan. Katanya, lelaki itu telah melampaui garis batas antara dunia manusia dan dunia lelembut. Saat pasang di hari senja, di mana terjadi percampuran antara dua sumber air menjadi satu, adalah pintu bagi manusia untuk memasuki dunia para lelembut. Dan mereka menyebut para penghuni alam lain itu dengan sebutan mambang.
Lelaki itu sendiri telah menyediakan kunci bagi dirinya untuk memasuki pekarangan para mambang itu.
senja
pasang
muara
Merupakan tiga unsur yang menyatu menjadi pelengkap sempurna perjalanan ajaibnya. Sebab, jiwa yang lemahlah sebagai penyebab akalnya menjadi ciut, dan kemudian menjadi linglung.
Merujuk dari kisah aneh beberapa tahun silam itulah, orang-orang kemudian berkesimpulan tentang nasib dan keberadaan Ineyah yang raib. Bahwasanya Ineyah pun kini dibawa pergi oleh makhluk tak kasat mata yang mendiami batas muara barang sekejap.
Sementara kerumunan perempuan berdesas-desus, maka kami selaku anak-anak merasa harus turut ambil bagian dalam misi pencarian Ineyah ini. Meski tak resmi dan bahkan tak pernah mendapatkan perintah secara langsung dari para orang tua, tetapi beberapa tempat yang kami curigai (sebagai anak-anak tentu saja), tak luput kami datangi. Mulai dari bagian dalam hutan, hingga ke bagian muara di dekat pulau lain yang berada di dekat pulau kampung kami. Dengan menaiki perahu, kami berkeliling dan melaporkan jika ada sesuatu yang menurut kami sebuah berita yang cukup berarti untuk diberikan pada orang yang lebih tua, agar selanjutnya diteruskan pada pak Maradi. Namun, sejauh ini semuanya masih nihil.
Memasuki hari ketiga, harapan seakan memudar. Pak Maradi sudah mendatangi beberapa ahli yang ia duga sanggup memberikan barang secuil berita mengenai keberadaan anaknya atau mengintip ke dalam air mangkuk tanah liat milik mereka. Meminta mereka menerawang mencari informasi, meski itu hanya informasi sehalus kabut di malam hari. Saat-saat itulah kegelisahan yang memuncak menguasai segenap pikirannya, yang memaksanya tidak berselera lagi menyantap makanan dan sedikit sekali menyesap minuman.
Seorang tua dari Pulau Besar kemudian datang bermalam beberapa hari di kediaman pak Maradi. Pria tua itu berselempang kain berwarna hitam di pundaknya. Giginya berwarna separuh kuning dan separuh merah. Ia terlihat selalu mengunyah, baik ketika sendiri, maupun ketika duduk bersama para pria yang berkumpul di rumah pak Maradi pada hari ke empat.
Pak Maradi sangat menghormati keberadaan lelaki tua itu. Saat ini ia hanya mendengarkan setiap ucapan yang keluar dari mulut yang selalu berlinang busa merah itu. Sepanjang yang kuketahui, lelaki itu adalah kerabat jauhnya yang juga seorang pemuka dalam dunia yang tak semua orang bisa mengunjunginya, yakni dunia arwah.
Maka dari titahnya, kemudian pak Maradi menyembelih beberapa ekor unggas. Lalu, darah unggas itu dikumpulkan dan dipercikkan di sebagian semak di ujung muara, dan sebagian lagi pada muka hutan yang terdapat batu besar. Ada juga beberapa butir telur yang ditempatkan di dalam keranjang kecil untuk dipusatkan di depan rumah, serta dijaga dengan sebentuk lampu kecil minyak kelapa, yang berlenggak-lenggok di kala malam tiba.
“Tunggulah hingga genap tujuh malam sejak perginya Ineyah, dan kalau mereka berkenan, maka anakmu akan menemukan jalan pulangnya sendiri.”
Demikian wasiat lelaki itu pada hari ke enam. Berarti tinggal menunggu sehari lagi kegelisahan pak Maradi akan menemukan titik ujungnya. Dan penantian sehari itu, terasa jauh lebih panjang dibanding hari-hari ketika ia ditinggal mati oleh isterinya. Sebab kematian merupakan sesuatu yang jelas dalam kehidupan. Ujung saat manusia kehilangan rasa kebahagiaan, tapi kemudian hidup harus dilanjutkan. Berbeda dengan saat penantian seperti ini, saat-saat ketidakjelasan menerka-nerka nasib yang tidak berwujud dalam bentuk yang nyata. Saat perasaan itu menggantung seperti awan hitam yang menaungi ke manapun pak Maradi melangkah pergi.
Dan begitulah, tepat keesokan harinya, pak Maradi berharap-harap cemas. Setiap berita yang datang dari orang yang baru pulang dijadikan pegangan. Setiap berita itu hadir, maka makin memuncak pula detak jantungnya. Ia tak lagi peduli apakah berita yang dibawa itu berkaitan dengan keberadaan anaknya ataupun tidak. Tetap saja ia berharap cemas.
Saat matahari berada di atas ubun-ubun, dan semua bayangan telah kehilangan sandarannya, pak Maradi masih berdiri di depan rumahnya. Ia tegak berdiri sekokoh batu karang. Lalu, nomatahari perlahan beranjak dari tempatnya. Cakrawala memerah. Beberapa saat kemudian kegelapan menyelimuti semuanya. Lampu-lampu minyak dinyalakan di setiap rumah. Pak Maradi bersikeras tetap berdiri di luar rumah, sembari menantikan kedatangan anaknya.
Dan saat malam benar-benar sepekat arang, ia berharap pertolongan itu segera tiba. Ia berharap kepada cahaya bulan untuk muncul, agar menjadi penerang jalan bagi anaknya yang mungkin berhasil keluar dari dunia para mambang yang membekap. Namun, ia pun menyadari, justru cahaya bulan yang muncul lebih menyeramkan di banding kegelapan. Sebab dalam keremangan itu, kemunculan berbagai sosok samar yang tak diketahuinya seakan menjelma menjadi sosok yang seolah-olah dikenalnya, tapi sosok itu berubah menjadi sosok lain dalam bentuk-bentuk baru. Begitulah, acap kali ia menyaksikan hal itu, semangatnya menyala dan kemudian mengendur. Rasa cemasnya diayun-ayun, naik dan turun, antara kegembiraan akan kembalinya Ineyah dan ketakutan akan kehilangan yang abadi.
Bulan kini telah naik sempurna memberikan penerangan yang lebih indah dari hari biasanya. Semua bayangan samar tadi semakin jelas di depan mata. Sosok yang ia kira bagai manusia yang sedang melangkah ke arahnya itu, tak lain adalah lambaian dahan pohon-pohon pisang yang miring di samping jalan, menciptakan tarian ketika ditiup oleh angin, dan rerimbunan pohon lain menciptakan lukisan kuning keperakan. Semua yang tak pernah ia perhatikan sebelumnya dan semua yang tak menarik perhatiannya kini ia perhatikan dengan seksama.
Rasa gemetar perlahan menyerang kakinya. Mula-mula betisnya terasa berkedut-kedut. Kemudian bergetar perlahan. Perutnya terasa turun dan diaduk-aduk. Menjalar pada bagian kepalanya. Sesaat kemudian ia limbung. Kakinya tak lagi kuat menopang tubuh dan dalam sekejap ia tersungkur ke tanah berpasir. Kepalanya jatuh menimpa telur-telur dalam keranjang. Semuanya pecah. Lampu minyak kelapa terpadam. Terkena lemak dari telur yang berserakan. Pak Maradi tumbang. Tubuhnya melorot seperti kain basah terjatuh dari jemuran.
Ia tak tahu sudah berapa lama dalam keadaan begitu. Segenap keluarganya tiba-tiba sudah berkumpul di ruang tengah rumahnya. Awalnya ia mendengar suara orang berbisik-bisik. Bayangan samar-samar melintas di matanya. Kemudian perlahan ia menguatkan diri. Bayangan samar itu perlahan menyatu dalam gerakan cepat yang menjelma menjadi sosok yang benar-benar dikenalnya semenjak masih berupa orok bayi yang cantik dan istrinya senang memanggilnya dengan panggilan si Bunga Melati. Sosok yang menjadi penyebab terkulai lemahnya ia di bilik kamarnya di tengah malam gulita. Di sana duduk dengan senyuman cemas di depannya.
Ineyah telah pulang!
Kepulangan Ineyah menciptakan kegaduhan baru di kampungku, tepat ketika pak Maradi tumbang tak sadarkan diri. Keluarganya dari dalam mendengar teriakan, dan ketika mereka dalam keadaan antara sadar dan tidak, menemukan Ineyah dalam keadaan memeluk ayahnya sambil tergugu menangis. Gadis itu menggoyang-goyangkan tubuh Ayahnya. Perasaan orang-orang yang meyaksikan itu terbelah menjadi dua, bahagia ketika melihat Ineyah pulang dalam keadaan bugar dan merasa cemas memikirkan keadaan pak Maradi. Adik-adiknya langsung menghambur memeluk Ineyah dan sesaat kemudian menangis saat memandang Ayah mereka. Beberapa keluarga yang masih bertahan di rumah itu memapah pak Maradi ke dalam dan dengan tergesa memeriksa napasnya dengan mendekatkan jari jemari ke lubang hidungnya.
“Ia hanya pingsan!” ujar salah seorang di antara mereka.
“Ia kelelahan setelah beberapa hari tidak makan. Sungguh, seandainya kau tidak pulang malam ini, aku tak tahu nasib apa yang menimpa adik-adikmu, Iney,” ujar yang lainnya.
Sementara pak Maradi dibaringkan di dalam biliknya, saudara paling muda dari Ayahnya mencecar Ineyah dengan pertanyaan-pertanyaan. Ineyah sendiri masih menunjukkan sikap diam tak bersuara. Ia lebih memilih menemani Ayahnya di dalam bilik. Salah seorang bibinya kemudian memegang kepalanya dan membelainya. Ineyah kemudian tergugu dan jatuh menangis dalam pelukannya. Tak lama kemudian gadis itu jatuh tertidur.
Orang tua bergigi kuning merah itu dilepas pulang dengan segenap penghormatan. Ia menolak ketika pak Maradi membekalinya dengan macam-macam barang. Yang kumaksud dengan macam-macam barang itu adalah beberapa ekor unggas dan beberapa bungkusan ikan asap, serta beberapa jenis ikan asin kering. Tampaknya ia merasa cukup puas dengan keberhasilannya memulangkan Ineyah dalam keadaan sehat dan tidak terganggu kewarasannya. Kehormatannya jauh di atas nilai yang dapat ditebus oleh sekadar unggas dan ikan asap.
Senyum sumringah tak pernah lepas dari wajah pak Maradi semenjak hari itu. Kegembiraannya telah kembali. Sejak itu Ineyah tak lagi bebas ke mana-mana. Ia selalu berada di dalam pengawasan bibinya yang kemudian tinggal beberapa waktu di rumahnya. Selain itu, di lehernya terlilit semacam kalung yang terbuat dari tali hitam dengan bandul semacam kerang. Pak Tua bergigi kuning itulah yang menganjurkan agar Ineyah selalu memakainya kapanpun dan di manapun. Hanya ketika ia melepas hajat saja kalung itu mesti ia tanggalkan.
Pak Maradi tak pernah lagi bertanya kepada Ineyah, ke mana ia dibawa oleh para mambang dalam waktu seminggu penuh. Sebab Ineyah sendiri selalu menunjukkan raut wajah yang aneh ketika mendapatkan pertanyaan semacam itu.
Namun, kegembiraan itu tak berlangsung lama. Beberapa bulan setelah peristiwa itu, kegemparan lain muncul di kampungku. Sumber masalahnya masih Ineyah. Kali ini bukan sebab ia hilang dibawa mambang, melainkan keadaan tubuhnya yang mengundang pertanyaan banyak orang. Mula-mula bibinya yang merasakan keganjilan itu. Sebagai wanita yang telah melahirkan banyak keturunan, tubuh Ineyah menunjukan tanda-tanda seperti orang yang hamil. Perutnya terlihat membuncit dan pinggulnya membengkak lebih besar dari biasanya. Ineyah kemudian mengurung diri di dalam kamarnya selama beberapa minggu kemudian.
Seperti biasa, desas-desuspun mengular ke sana ke mari bagaikan lidah api yang berjuluran mencari serabut yang mudah untuk dijilat dan kemudian terbakar. Setelah melalui paksaan dan bermacam ancaman, Ineyah akhirnya dengan muram bercerita, bahwa ia sesungguhnya tak pernah dilarikan oleh mambang penghuni muara. Ia sendiri yang telah menentukan nasibnya pada malam ketika ia menghilang. Ternyata ia melarikan diri dari rumahnya tepat di malam hari ketika musim pasang. Terpengaruh dari cerita orang hilang yang pernah ia dengar sebelumnya, ia kemudian dijemput oleh Inggil Wilika, seorang lelaki penyadap pelepah nira, yang ternyata telah menjalin kasih dengannya selama beberapa waktu.
Mereka memanfaatkan celah waktu sesudah belajar rupa-rupa keahlian pada Ibuku di sore hari, dan baru pulang pada saat senja menjelang. Di antara waktu itulah mereka sering melewatkan waktu berdua. Ketika air pasang tiba, rencana kasih mereka menemukan muaranya. Andai saja perut Ineyah tak membesar, pastilah kisah penculikan oleh mambang ini akan diceritakan dari generasi ke generasi berikutnya dengan perasaan takut.
Beberapa waktu kemudian Inggil dihadapkan dalam rapat adat desa. Di rumah besar, mereka berdua dihadapkan. Setengah anggota keluarga Ineyah, termasuk Ayah dan saudara laki-lakinya membentuk setengah lingkaran. Anggota keluarga lelaki ‘penculik’ itu juga membentuk setengah lingkaran yang sama di seberang mereka. Kedua keluarga itu dipisahkan oleh pembatas di tengah ruangan. Aura kemarahan dan ketakutan kentara di dalamnya. Namun, tertutupi oleh ketegasan dan wibawa para pemuka.
Setelah pertemuan itu, diputuskanlah nasib mereka. Keluarga Inggil Wilika diwajibkan membayar denda berupa dua ekor sapi betina untuk desa. Beberapa ratus keping uang untuk keluarga pak Maradi. Lalu keduanya dikawinkan dalam beberapa hari sesudah itu, akan tetapi mereka tidak diperbolehkan tinggal di kampung tersebut selama beberapa tahun. Pak Maradi tak dapat menolak keputusan itu, meski di dalam hatinya merasa sedih karena ditinggal oleh anak perempuannya. Namun, rasa malu telah lebih dahulu menutup hatinya.
Ibuku, dalam kelembutannya, memberi nasihat penting padaku, “usah kau percaya dukun-dukun dan segala cerita mambang itu, Landu. Sebab, manusia jauh lebih celaka kelakuannya daripada mambang paling jahat sekalipun.”
Aku mengangguk takzim, sembari masih memikirkan bagaimana perasaan pak Maradi saat ia menyadari hampir kehilangan anaknya yang disangkanya telah dilarikan oleh para mambang, meski akhirnya kembali dalam keadaan selamat. Lalu, tiba-tiba saja rasa senangnya tercerabut dan terhempas lagi berkeping-keping, disebabkan keganasan penyakit yang ditiupkan oleh syetan di dalam mantra dan sajak indahnya. Penyakit yang diselimuti dengan kata-kata indah, nan memabukkan:
CINTA.
Panji Prasetya, Pegiat Komunitas Speak Forward dan Public Speaking Coach.